SMJTimes.com – Di era media sosial, kebahagiaan sering kali ditampilkan seolah menjadi kewajiban. Ucapan semua pasti akan baik-baik saja terdengar seperti menenangkan di permukaan, tetapi justru menjadi pendorong terbentuknya toxic positivity atau dorongan untuk selalu positif meskipun sedang sakit.
Fenomena ini bahkan semakin marak sejak budaya self improvement dan arus motivasi digital merebak di berbagai platform. Unggahan bertema semangat hidup dan healing yang digunakan secara berlebihan, justru dapat menekan emosi alami seseorang.
Dampaknya, banyak orang berusaha menutupi perasaan sebenarnya demi terlihat positif di mata orang lain. Di lingkungan kerja, hal ini sering muncul dalam bentuk semangat meski sedang burnout, sementara di kehidupan pribadi berwujud menahan tangis dengan dalih tidak ingin terlihat lemah.
Padahal, terus-menerus menekan emosi bisa menyebabkan stres kronis, kelelahan mental, bahkan emotional numbness atau kondisi ketika seseorang tidak lagi bisa merasakan apa pun secara mendalam atau bahkan sering disebut mati rasa.
Menurut laporan Harvard Health Publishing (2024), kunci kesehatan mental justru ada pada penerimaan emosi, bukan penolakannya. Mengakui bahwa sedang sedih atau lelah bukan berarti kita pesimis, tetapi sedang berproses untuk memahami diri.
Untuk menghindari toxic positivity, cobalah untuk tidak langsung memberikan kalimat penyemangat ketika seseorang sedang curhat. Sebaliknya, dengarkan dulu tanpa menghakimi. Memberi validasi perasaan lebih dianjurkan daripada meminta untuk tidak dipikirkan.
Karena kebahagiaan sejati tidak datang dari menolak rasa sakit, tetapi dari kemampuan menerima bahwa hidup tak selalu berjalan mulus. (*)






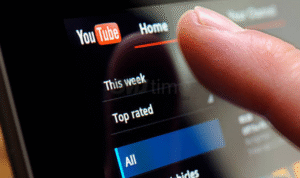





Komentar